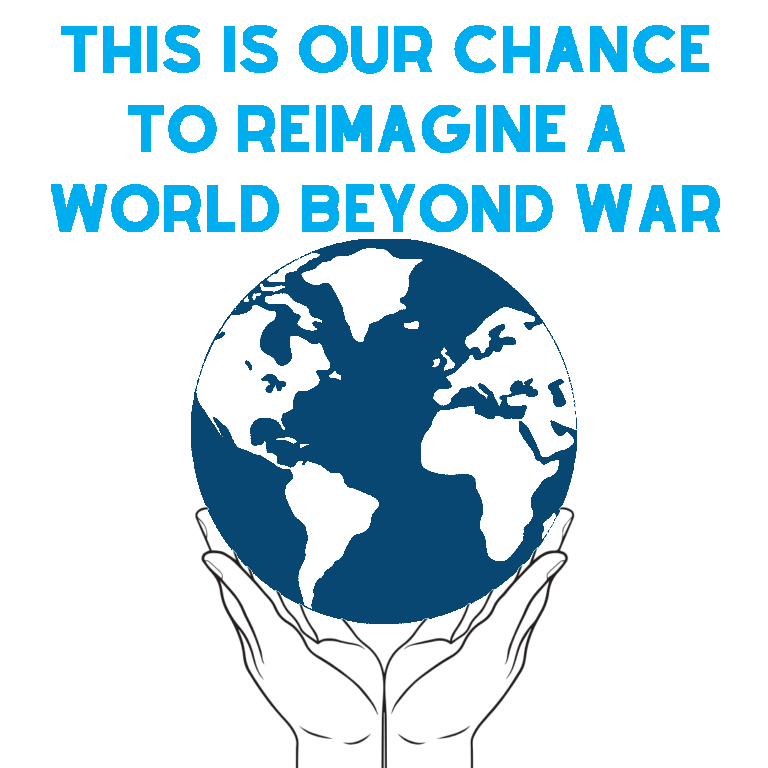Oleh Joseph Essertier, World BEYOND War, 29 Maret, 2021
"Merupakan tugas para ahli hukum untuk memverifikasi bahwa aturan Konstitusi dihormati, tetapi para ahli hukum diam."
Giorgio Agamben, "Sebuah Pertanyaan," Dimana kita sekarang? Epidemi sebagai Politik (2020)
Seperti "9/11" di Amerika Serikat, "3/11" Jepang adalah momen penting dalam sejarah manusia. 3/11 adalah singkatan dari gempa bumi dan tsunami Tōhoku yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 yang memicu Bencana Nuklir Fukushima Daiichi. Keduanya adalah tragedi yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang luar biasa, dan dalam kedua kasus tersebut, sebagian dari hilangnya nyawa tersebut adalah akibat dari tindakan manusia. 9/11 mewakili kegagalan banyak warga AS; 3/11 mewakili kegagalan banyak warga Jepang. Ketika kaum progresif AS mengingat kembali setelah 9/11, banyak yang berpikir tentang pelanggaran hukum negara dan pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh Patriot Act. Demikian pula bagi banyak orang progresif Jepang, pelanggaran hukum negara dan pelanggaran hak asasi manusia akan muncul di benak mereka ketika mereka mengingat 3/11. Dan bisa dikatakan bahwa 9/11 dan 3/11 mengakibatkan pelanggaran hak-hak orang Jepang. Misalnya, meningkatnya ketakutan akan terorisme setelah 9/11 memberikan momentum yang lebih besar kepada kaum konservatif untuk merevisi konstitusi dengan alasan "situasi internasional yang berubah dengan cepat di sekitar Jepang"; Jepang menjadi terlibat dalam perang di Afghanistan dan Irak; dan ada peningkatan pengawasan orang di Jepang setelah 9/11 sama seperti di negara lain. Satu serangan teroris dan yang lainnya bencana alam, tetapi keduanya telah mengubah jalannya sejarah.
Sejak diundangkan, telah terjadi pelanggaran terhadap Konstitusi Jepang, namun mari kita gunakan kesempatan ini untuk meninjau kembali beberapa pelanggaran hukum negara dan pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tiga krisis 9/11, 3/11, dan COVID-19. Saya berpendapat bahwa kegagalan untuk menuntut, memperbaiki, atau menghentikan pelanggaran Konstitusi pada akhirnya akan melemahkan dan mengikis otoritas Konstitusi, dan melunakkan warga Jepang untuk revisi konstitusi ultranasionalis.
Pasca-9/11 Pelanggaran hukum
Pasal 35 melindungi hak orang-orang "untuk merasa aman di rumah, dokumen, dan efek mereka terhadap entri, penggeledahan, dan penyitaan". Tapi Pemerintah sudah dikenal mata-mata pada orang yang tidak bersalah, terutama pada komunis, Korea, dan Muslim. Mata-mata seperti itu oleh pemerintah Jepang selain kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pemerintah AS (dijelaskan oleh Edward Snowden dan Julian Assange), yang tampaknya diizinkan oleh Tokyo. Penyiar publik Jepang NHK dan The Intercept telah mengungkap fakta bahwa agen mata-mata Jepang, “Direktorat Intelijen Sinyal atau DFS, mempekerjakan sekitar 1,700 orang dan memiliki setidaknya enam fasilitas pengawasan yang menguping sepanjang waktu untuk panggilan telepon, email, dan komunikasi lainnya ”. Kerahasiaan seputar operasi ini menyebabkan orang bertanya-tanya seberapa "aman" orang Jepang di rumah mereka.
Seperti yang ditulis Judith Butler pada tahun 2009, “Nasionalisme di AS, tentu saja, telah meningkat sejak serangan 9/11, tetapi mari kita ingat bahwa ini adalah negara yang memperluas yurisdiksinya di luar perbatasannya sendiri, yang menangguhkan kewajiban konstitusionalnya. di dalam perbatasan tersebut, dan yang memahami dirinya sebagai pengecualian dari sejumlah perjanjian internasional. " (Bab 1 tentang dia Kerangka Perang: Kapan Hidup Menyedihkan?) Bahwa pemerintah AS dan para pemimpin Amerika terus-menerus membuat pengecualian untuk diri mereka sendiri dalam hubungan mereka dengan negara lain didokumentasikan dengan baik; orang Amerika pro-perdamaian sadar hambatan perdamaian ini. Beberapa orang Amerika juga sadar bahwa pejabat pemerintah kita, baik Partai Republik maupun Demokrat, menangguhkan kewajiban konstitusional negara kita ketika mereka menyetrika dan sebaliknya menghidupkan kembali Undang-Undang Patriot. Bahkan ketika mantan Presiden Trump yang tidak populer "melontarkan gagasan untuk menjadikan kekuatan pengawasan pemerintah permanen," ada “Tidak ada protes dari siapa pun tentang dampaknya terhadap hak-hak rakyat Amerika”.
Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa Washington mengekspor histeria 9/11 negara kita ke negara lain, bahkan mendorong pemerintah lain untuk melanggar konstitusi mereka sendiri. “Tekanan terus-menerus dari pejabat senior pemerintah AS merupakan faktor penting yang mendorong Jepang untuk memperketat undang-undang kerahasiaannya. Perdana Menteri [Shinzo] Abe telah berulang kali menyatakan bahwa kebutuhan akan undang-undang kerahasiaan yang lebih ketat sangat diperlukan rencana untuk membuat Dewan Keamanan Nasional berdasarkan model Amerika ”.
Jepang mengikuti jejak AS pada Desember 2013 ketika Diet (yaitu, majelis nasional) mengeluarkan kontroversi Bertindak tentang Perlindungan Rahasia yang Ditunjuk Khusus. Hukum ini berpose sebuah “ancaman berat terhadap pelaporan berita dan kebebasan pers di Jepang. Pejabat pemerintah tidak pernah menghindar dari mengintimidasi wartawan di masa lalu. Undang-undang baru akan memberi mereka kekuatan yang lebih besar untuk melakukannya. Pengesahan undang-undang tersebut memenuhi tujuan lama pemerintah untuk mendapatkan pengaruh tambahan atas media berita. Undang-undang baru itu bisa berdampak layu pada pelaporan berita dan dengan demikian pada pengetahuan masyarakat tentang tindakan pemerintah mereka. "
“Amerika Serikat memiliki angkatan bersenjata dan hukum untuk melindungi rahasia negara. Jika Jepang ingin melakukan operasi militer bersama dengan Amerika Serikat, ia harus mematuhi undang-undang kerahasiaan AS. Inilah yang melatarbelakangi usulan undang-undang kerahasiaan. Namun, RUU tersebut mengungkapkan niat pemerintah untuk memperluas cakupan undang-undang lebih luas dari itu. "
Jadi 9/11 adalah kesempatan bagi pemerintah ultranasionalis di Jepang untuk mempersulit warga negara untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, bahkan saat memata-matai mereka lebih dari sebelumnya. Dan, nyatanya, tidak hanya rahasia pemerintah dan privasi masyarakat menjadi isu setelah 9/11. Seluruh Konstitusi Perdamaian Jepang menjadi masalah. Yang pasti, kaum konservatif Jepang bersikeras pada revisi konstitusi karena "kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang besar" dan "kondisi politik yang tidak menentu di Semenanjung Korea." Tetapi "ketakutan yang meluas akan terorisme di Amerika Serikat dan Eropa" juga a faktor.
Pelanggaran Pasca-3/11
Selain kerusakan langsung yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami tahun 2011, terutama tiga "lelehan-throughs" nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi telah membocorkan radiasi ke lingkungan alam sekitarnya sejak hari yang menentukan itu. Namun Pemerintah berencana membuang satu juta ton air yang terkontaminasi tritium dan racun lainnya, mengabaikan tentangan dari ilmuwan, pemerhati lingkungan, dan kelompok nelayan. Tidak diketahui berapa banyak kematian di Jepang atau di negara lain akibat serangan alam ini. Pesan dominan dari media massa tampaknya adalah bahwa penyerangan ini tidak dapat dihindari karena pembersihan yang tepat akan merepotkan dan mahal bagi Tokyo Electric Power Company (TEPCO), yang menerima banyak dukungan dari Pemerintah. Siapapun dapat melihat bahwa serangan seperti itu di Bumi harus dihentikan.
Segera setelah 3/11, pemerintah Jepang dihadapkan pada masalah besar. Memang ada semacam batasan hukum tentang seberapa banyak keracunan lingkungan dapat ditoleransi. Ini adalah undang-undang yang menetapkan "paparan radiasi tahunan yang diizinkan secara hukum". Jumlah maksimum adalah satu milisievert per tahun untuk orang-orang yang tidak bekerja di industri tersebut, tetapi karena hal itu akan merepotkan TEPCO dan Pemerintah, karena untuk mematuhi undang-undang tersebut diperlukan evakuasi sejumlah besar orang yang tidak dapat diterima dari daerah-daerah yang sebelumnya. terkontaminasi oleh radiasi nuklir, Pemerintah begitu saja berubah angka itu menjadi 20. Voila! Masalah terpecahkan.
Tetapi tindakan bijaksana yang memungkinkan TEPCO mencemari perairan di luar pantai Jepang (tentu saja setelah Olimpiade) akan merusak semangat Pembukaan Konstitusi, terutama kata-kata “Kami mengakui bahwa semua orang di dunia memiliki hak untuk tinggal di damai, bebas dari rasa takut dan keinginan. " Menurut Gavan McCormack, “Pada September 2017, TEPCO mengakui bahwa sekitar 80 persen air yang disimpan di situs Fukushima masih mengandung zat radioaktif di atas level legal, strontium, misalnya, lebih dari 100 kali level yang diizinkan secara legal.”
Lalu ada para pekerja, mereka yang “dibayar untuk terpapar” radiasi di Fukushima Daiichi dan pabrik lainnya. “Dibayar untuk diekspos” adalah kata-kata Kenji HIGUCHI, jurnalis foto terkenal yang pernah melakukannya terkena pelanggaran hak asasi manusia di industri tenaga nuklir selama beberapa dekade. Untuk hidup bebas dari rasa takut dan keinginan, orang membutuhkan lingkungan alam yang sehat, tempat kerja yang aman, dan pendapatan dasar atau minimum, tetapi "gipsi nuklir" Jepang tidak menikmati semua itu. Pasal 14 menetapkan bahwa "Semua orang sederajat di bawah hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau asal usul keluarga." Pelecehan terhadap pekerja Fukushima Daiichi telah didokumentasikan dengan cukup baik bahkan di media massa, tetapi itu terus berlanjut. (Reuters, misalnya, telah menghasilkan sejumlah eksposur, seperti yang ini).
Diskriminasi memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Ada bukti bahwa "orang-orang yang direkrut di pembangkit listrik tenaga nuklir bukan lagi petani," bahwa mereka adalah Burakumin (yaitu, keturunan kasta Jepang yang distigmatisasi, seperti Dalit dari India), Korea, imigran Brasil dari keturunan Jepang, dan lainnya yang secara berbahaya “hidup di pinggiran ekonomi”. "Sistem subkontrak untuk tenaga kerja manual di fasilitas tenaga nuklir" adalah "diskriminatif dan berbahaya". Higuchi mengatakan bahwa "seluruh sistem didasarkan pada diskriminasi."
Sejalan dengan Pasal 14, Undang-Undang Ujaran Kebencian disahkan pada tahun 2016, namun ompong. Kejahatan kebencian terhadap minoritas seperti Korea dan Okinawa seharusnya ilegal sekarang, tetapi dengan undang-undang yang lemah, Pemerintah dapat membiarkannya berlanjut. Seperti yang dikatakan oleh aktivis hak asasi manusia Korea SHIN Sugok, “Ekspansi kebencian terhadap Zainichi Korea [yaitu, migran dan keturunan orang-orang yang berasal dari kolonial Korea] menjadi lebih serius. Internet punya menjadi sarang ujaran kebencian ”.
Status Pengecualian Pandemi
Baik 9/11 tahun 2001 dan bencana alam 3/11 tahun 2011, mengakibatkan pelanggaran konstitusional yang berat. Sekarang, kira-kira satu dekade setelah 3/11, kami melihat pelanggaran berat lagi. Kali ini mereka disebabkan oleh pandemi, dan orang dapat membantah bahwa mereka sesuai dengan definisi "keadaan pengecualian". (Untuk sejarah singkat dari "keadaan pengecualian," termasuk bagaimana Reich Ketiga yang berlangsung selama dua belas tahun muncul, lihat ini). Sebagai Profesor Studi Hak Asasi Manusia dan Perdamaian Saul Takahashi berdebat pada bulan Juni 2020, "COVID-19 mungkin terbukti hanya menjadi pengubah permainan yang perlu didorong oleh perdana menteri Jepang melalui agendanya untuk merevisi Konstitusi". Elite ultranasionalis di pemerintahan sibuk bekerja mengeksploitasi krisis demi keuntungan politik mereka sendiri.
Undang-undang baru, radikal, dan kejam tiba-tiba diberlakukan bulan lalu. Harus ada tinjauan menyeluruh dan sabar oleh para ahli serta debat di antara warga negara, cendekiawan, ahli hukum, dan anggota Diet. Tanpa partisipasi dan debat yang melibatkan masyarakat sipil, beberapa orang Jepang menjadi frustrasi. Misalnya, video protes jalanan dapat dilihat di sini. Beberapa orang Jepang sekarang mempublikasikan pandangan mereka, bahwa mereka tidak serta merta menyetujui pendekatan Pemerintah untuk mencegah penyakit dan melindungi yang rentan, atau untuk healing untuk hal tersebut.
Dengan bantuan krisis pandemi, Jepang tergelincir dan meluncur ke arah kebijakan yang dapat melanggar Pasal 21 Konstitusi. Sekarang di tahun 2021, artikel itu hampir terdengar seperti aturan yang tidak jelas dari zaman dulu: “Kebebasan berkumpul dan berserikat serta berbicara, pers dan semua bentuk ekspresi lainnya dijamin. Tidak ada sensor yang akan dipertahankan, dan kerahasiaan sarana komunikasi apa pun tidak boleh dilanggar. "
Pengecualian baru untuk Pasal 21 dan (salah) pengakuan keabsahannya dimulai tahun lalu pada tanggal 14 Maret, ketika Diet memberikan mantan Perdana Menteri Abe "otoritas hukum untuk menyatakan 'keadaan darurat' atas epidemi Covid-19". Sebulan kemudian dia memanfaatkan otoritas baru itu. Selanjutnya, Perdana Menteri SUGA Yoshihide (anak didik Abe) mengumumkan keadaan darurat kedua yang mulai berlaku pada 8 Januari tahun ini. Dia hanya dibatasi sejauh dia harus "melaporkan" deklarasinya ke Diet. Dia memiliki kewenangan, berdasarkan penilaian pribadinya sendiri, untuk menyatakan keadaan darurat. Ini seperti dekrit dan memiliki efek hukum.
Sarjana hukum tata negara, TAJIMA Yasuhiko, membahas inkonstitusionalitas dari deklarasi darurat pertama dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 10 April tahun lalu (di majalah progresif Shūkan Kin'yōbi, halaman 12-13). Dia dan pakar hukum lainnya menentang undang-undang yang menyerahkan kekuasaan ini kepada perdana menteri. (Hukum ini telah disebut untuk sebagai Hukum Tindakan Khusus dalam bahasa Inggris; dalam bahasa Jepang Shingata infuruenza untuk taisaku tokubetsu sochi hō:).
Kemudian pada tanggal 3 Februari tahun ini beberapa undang-undang COVID-19 baru dibuat Lulus dengan pemberitahuan singkat tentang mereka yang diberikan kepada publik. Di bawah undang-undang ini, pasien COVID-19 yang menolak rawat inap atau orang "yang tidak bekerja sama dengan pejabat kesehatan masyarakat yang melakukan tes atau wawancara infeksi" akan wajah denda sebesar ratusan ribu yen. Kepala salah satu pusat kesehatan Tokyo mengatakan bahwa daripada mendenda orang yang menolak dirawat di rumah sakit, Pemerintah harus melakukannya memperkuat “sistem pusat kesehatan dan fasilitas medis”. Sementara fokus sebelumnya adalah pada hak orang sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sekarang fokusnya adalah pada kewajiban orang sakit untuk menerima perawatan medis yang didorong atau disetujui oleh Pemerintah. Pergeseran serupa dalam kebijakan dan pendekatan kesehatan terjadi di sejumlah negara di seluruh dunia. Dalam kata-kata Giorgio Agamben, “warga negara tidak lagi memiliki 'hak atas kesehatan' (keselamatan kesehatan), tetapi menjadi wajib secara hukum atas kesehatan (biosekuriti)” (“Biosecurity and Politics,” Dimana kita sekarang? Epidemi sebagai Politik, 2021). Satu pemerintahan dalam demokrasi liberal, Pemerintah Jepang, jelas memprioritaskan biosekuriti daripada kebebasan sipil. Biosecurity berpotensi memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan kekuasaan mereka atas masyarakat Jepang.
Untuk kasus di mana orang sakit yang memberontak tidak bekerja sama, awalnya ada rencana untuk "hukuman penjara hingga satu tahun atau denda hingga 1 juta yen (9,500 dolar AS)," tetapi beberapa suara di dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi berargumen bahwa hukuman semacam itu akan sedikit "terlalu berat", jadi rencana itu memang demikian dihapus. Bagi para penata rambut yang tidak kehilangan mata pencaharian dan entah bagaimana masih bisa mendapatkan penghasilan 120,000 yen per bulan, denda beberapa ratus ribu yen dianggap pantas.
Di beberapa negara, kebijakan COVID-19 telah mencapai titik di mana "perang" telah diumumkan, keadaan pengecualian yang ekstrim, dan dibandingkan dengan beberapa pemerintah liberal dan demokratis, pengecualian konstitusional Jepang yang baru dilembagakan mungkin tampak ringan. Di Kanada, misalnya, seorang jenderal militer telah dipilih untuk memimpin a perang tentang virus SARS-CoV-2. "Semua pelancong yang memasuki negara tersebut" diharuskan untuk mengkarantina diri mereka sendiri selama 14 hari. Dan mereka yang melanggar karantina mereka bisa dihukum dengan denda hingga "$ 750,000 atau sebulan penjara". Orang Kanada memiliki AS di perbatasan mereka, perbatasan yang sangat panjang dan sebelumnya keropos, dan dapat dikatakan bahwa pemerintah Kanada sedang mencoba untuk menghindari "nasib virus korona Amerika Serikat." Tetapi Jepang adalah negara kepulauan yang perbatasannya lebih mudah dikendalikan.
Terutama di bawah pemerintahan Abe, tetapi selama dekade dua puluh remaja (2011-2020), para penguasa Jepang, sebagian besar LDP, telah mendorong Konstitusi Perdamaian liberal, yang dibuat pada tahun 1946 ketika orang Jepang mendengar kata-kata, "Pemerintah Jepang mengumumkan konstitusi perdamaian pertama dan satu-satunya di dunia, yang juga akan menjamin hak asasi manusia dasar rakyat Jepang ”(Bisa dilihat cuplikan dokumenter pengumumannya di 7:55 di sini). Selama dua puluh remaja, daftar pasal yang telah dilanggar selama dekade terakhir, di luar pasal yang dibahas di atas (14 dan 28), akan mencakup Pasal 24 (persamaan dalam pernikahan), Pasal 20 (pemisahan gereja dan negara), dan tentu saja, permata mahkota dari perspektif gerakan perdamaian dunia, Pasal 9: “Mencita-citakan dengan tulus perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, kekuatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya tidak akan pernah dipertahankan. Hak berperang negara tidak akan diakui. "
Jepang? Demokratis dan damai?
Sejauh ini, Konstitusi sendiri mungkin telah memeriksa kemerosotan pemerintahan otoriter oleh perdana menteri ultranasionalis Abe dan Suga. Tetapi ketika seseorang mempertimbangkan pelanggaran konstitusional dekade terakhir ini, setelah krisis besar terakhir 3/11 dan Fukushima Daiichi, seseorang melihat dengan jelas bahwa otoritas "konstitusi perdamaian pertama dan satu-satunya di dunia" telah diserang selama bertahun-tahun. Yang paling menonjol di antara para penyerang adalah kaum ultranasionalis di Partai Demokrat Liberal (LDP). Dalam konstitusi baru yang mereka buat pada April 2012, mereka tampaknya membayangkan akhir dari "eksperimen Jepang pascaperang dalam demokrasi liberal," menurut kepada profesor hukum Lawrence Repeta.
LDP memiliki visi yang besar dan mereka tidak merahasiakannya. Dengan banyak pandangan ke depan pada tahun 2013 Repeta membuat daftar dari “sepuluh proposal LDP yang paling berbahaya untuk perubahan konstitusional”: menolak universalitas hak asasi manusia; meningkatkan pemeliharaan "ketertiban umum" atas semua hak individu; menghilangkan perlindungan kebebasan berbicara untuk kegiatan “dengan tujuan merusak kepentingan umum atau ketertiban umum, atau berhubungan dengan orang lain untuk tujuan tersebut”; menghapus jaminan komprehensif dari semua hak konstitusional; serangan terhadap "individu" sebagai fokus hak asasi manusia; tugas baru untuk rakyat; menghalangi kebebasan pers dan kritik terhadap pemerintah dengan melarang “perolehan, kepemilikan, dan penggunaan informasi yang salah terkait dengan seseorang”; pemberian perdana menteri kekuatan baru untuk menyatakan "keadaan darurat" ketika pemerintah dapat menangguhkan proses konstitusional biasa; berubah menjadi artikel sembilan; dan menurunkan standar untuk amandemen konstitusi. (Kata-kata Repeta; huruf miring saya).
Repeta menulis pada 2013 bahwa tahun itu adalah "momen kritis dalam sejarah Jepang". Tahun 2020 mungkin merupakan momen kritis lainnya, karena ideologi biosekuriti yang berpusat pada negara dan "keadaan pengecualian" yang memberdayakan oligarki berakar. Kita juga harus merenungkan kasus Jepang pada tahun 2021, sebagai contoh kasus, dan membandingkan perubahan hukum yang terjadi pada zamannya dengan yang terjadi di negara lain. Filsuf Giorgio Agamben memperingatkan kita tentang keadaan pengecualian pada tahun 2005, menulis bahwa “totalitarianisme modern dapat didefinisikan sebagai pembentukan, melalui keadaan pengecualian, dari perang sipil legal yang memungkinkan penghapusan fisik tidak hanya dari musuh politik tetapi dari seluruh kategori warga negara yang karena alasan tertentu tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik… Penciptaan keadaan darurat permanen secara sukarela… telah menjadi salah satu praktik penting dari negara-negara kontemporer, termasuk apa yang disebut sebagai yang demokratis. ” (Dalam Bab 1 “Keadaan Pengecualian sebagai Paradigma Pemerintahan” nya Keadaan Pengecualian2005, halaman 2).
Berikut ini adalah beberapa contoh deskripsi Jepang saat ini oleh para intelektual dan aktivis publik terkemuka: "sebuah negara 'ekstrim kanan', tunduk pada 'fasisme ketidakpedulian' di mana para pemilih Jepang seperti katak yang perlahan-lahan memanaskan air fasis, tidak lagi hukum- diatur atau demokratis tetapi bergerak ke arah menjadi 'masyarakat gelap dan negara fasis,' di mana 'korupsi fundamental politik' menyebar melalui setiap sudut dan celah masyarakat Jepang, saat itu memulai 'penurunan tajam menuju keruntuhan peradaban' ”. Bukan potret bahagia.
Berbicara tentang tren global, Chris Gilbert punya tertulis bahwa "minat masyarakat kita yang memudar dalam demokrasi mungkin terlihat jelas selama krisis Covid yang sedang berlangsung, tetapi ada banyak bukti bahwa seluruh dekade terakhir telah melibatkan gerhana sikap demokratis". Ya, hal yang sama berlaku di Jepang. Status pengecualian, undang-undang yang kejam, penangguhan supremasi hukum, dll. Telah menyatakan di sejumlah negara demokrasi liberal. Di Jerman musim semi lalu, misalnya, bisa jadi didenda untuk membeli buku di toko buku, pergi ke taman bermain, melakukan kontak dengan seseorang di depan umum yang bukan anggota keluarga, mendekat dari 1.5 meter dengan seseorang saat sedang mengantre, atau memotong rambut teman di halaman.
Tendensi militeristik, fasistik, patriarkal, femisidal, ekosidal, monarki, dan ultranasionalis mungkin dapat diperkuat oleh kebijakan COVID-19 yang kejam, dan itu hanya akan mempercepat keruntuhan peradaban pada momen sejarah ini, ketika kita harus selalu sadar bahwa yang kita hadapi, di atas semuanya, dua ancaman eksistensial: perang nuklir dan pemanasan global. Untuk menghilangkan ancaman ini, kita membutuhkan kewarasan, solidaritas, keamanan, kebebasan sipil, demokrasi, dan tentunya kesehatan dan kekebalan yang kuat. Kita tidak boleh mengesampingkan keyakinan progresif inti kita dan membiarkan pemerintah membongkar konstitusi yang melindungi perdamaian dan hak asasi manusia yang tidak nyaman. Orang Jepang dan orang lain di seluruh dunia membutuhkan Konstitusi Perdamaian Jepang yang unik sekarang lebih dari sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang harus ditiru dan dikembangkan di seluruh dunia.
Semua ini untuk mengatakan, mengikuti Tomoyuki Sasaki, “Konstitusi harus dipertahankan”. Untungnya, mayoritas tipis tetapi mayoritas tetap sama, orang Jepang masih menghargai konstitusi mereka dan menentang revisi yang diusulkan LDP.
Terima kasih banyak kepada Olivier Clarinval yang telah menjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana kebijakan kesehatan pemerintah saat ini di Dunia Utara mengancam demokrasi.
Joseph Essertier adalah associate professor di Institut Teknologi Nagoya di Jepang.